Catatan Hari Kebangkitan Nasional 2011
Bagian pertama dari Dua Tulisan
Bagian pertama dari Dua Tulisan
Alkisah, seorang kakek terperosok di sebuah parit di tepi jalan desa. Kakek itu pun merintih kesakitan seraya meminta tolong. Tak lama kemudian, seorang tokoh masyarakat melewati jalan tersebut. Mendengar rintihan meminta tolong, sang tokoh menghentikan langkahnya dan bergegas mendekati kakek tersebut. Sesaat setelah mengamati keadaan sang kakek, sembari melihat jam tangannya, tokoh tersebut berkata, ”Mohon maaf, Kek. Saya ingin menolong kakek tapi saya telah ditunggu oleh Kepala Desa untuk membicarakan program pembangunan desa, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kakek tenang saja, nanti pasti ada orang yang lewat yang akan menolong kakek. Permisi.” Dan pergilah sang tokoh meninggalkan kakek yang masih terus merintih kesakitan.
Tak lama berselang, muncullah seorang tokoh agama. Setelah mengamati keadaan sang kakek, tokoh agama itu berujar, ”Mohon maaf, Kek. Saya ingin menolong kakek tapi saya telah ditunggu oleh jama’ah saya yang telah menanti sejak tadi. Ini pengajian bulanan jadi mereka telah menunggu sebulan lamanya untuk mendengarkan ceramah saya. Kakek tenang saja, nanti pasti ada orang lewat yang akan menolong kakek. Permisi.” Dan pergilah sang tokoh meninggalkan kakek sendirian.
Beberapa saat kemudian, lewatlah di jalan tersebut seorang pemulung berbaju lusuh. Mendengar rintihan meminta tolong, pemulung itu bergegas mendekat, kantong plastik dan batang besi dicampakkannya ke tanah, dan segera menolong kakek tersebut serta membawanya ke rumah penduduk terdekat. Setelah memastikan sang kakek mendapat pertolongan, pemulung itu mengambil barang-barangnya dan kembali meneruskan pekerjaannya: mencari sampah yang bisa dijual untuk membeli beras dan lauk untuk anak dan istrinya yang setia menunggu di rumah.
Momen yang Tepat
Ada hal mendasar yang ingin penulis sampaikan melalui ilustrasi di atas, yaitu momen. Tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih memilih untuk melayani masyarakat yang menunggu mereka dengan dalih bahwa menolong kakek itu bukanlah momen yang tepat. Selain urusan masyarakat yang mereka anggap lebih penting daripada sekadar menolong seorang kakek, mereka meyakini bahwa akan datang orang lain yang akan melakukan pekerjaan itu.
Momen yang tepat. Itulah kata sakti yang sering ditunggu oleh banyak orang untuk melakukan sesuatu, tidak terkecuali oleh generasi muda. Seringkali kita temui generasi muda, yang umumnya terdidik, yang belum juga mau terjun ke masyarakat karena ”menunggu momen yang tepat”. Pilihan yang tidak sepenuhnya salah. Tetapi, perlu juga disadari bahwa proses menunggu tidak lantas membuat jarum jam berhenti berdetak sementara gerak dan geliat dinamika masyarakat amatlah dinamis.
Di sisi lain, terkadang juga kita temui generasi muda yang pada akhirnya lebih memilih mundur dari ”gelanggang pertempuran” dengan dalih bahwa masyarakat telah terlanjur rusak sehingga ia yang mencoba hadir sebagai agent of change, agen perubahan-sebutan yang amat dibanggakan hasil produksi kampus-ternyata tak mampu merubah apapun di masyarakat. Idealisme yang dibawa dari kampus nan megah, sumber referensi dari aneka buku, diktat, modul, dan karya ilmiah, serta teori-teori panjang lebar yang dengan susah payah telah dihafalkan, ternyata menjadi teramat abstrak manakala hendak diimplementasikan di kehidupan nyata.
Di kampus, yang haru-biru oleh gegap gempita semangat perubahan lengkap dengan teriakan dan acungan tangan mengepal, idealisme adalah kenyataan. Dan merupakan sebuah harga mati yang tak lagi bisa ditawar. Di masyarakat? Aneka kenyataan kemudian seringkali berujung pada kesimpulan singkat: untuk bertahan hidup, kenyataan adalah idealisme. Dan tenggelamlah sang agen perubahan pada pertempuran batin yang nyaris tanpa jeda. Tanpa ujung. Tidak sedikit yang menyerah kalah dan terkapar di titik frustrasi.
Tak adakah celah di antara dua pilihan itu? Apakah pilihan untuk memperjuangkan idealisme di masyarakat adalah semata-mata pilihan antara benar dan salah, antara hitam dan putih? Menurut penulis, ada. Memperjuangkan idealisme memang sebuah keniscayaan. Tetapi, kenyataan yang dihadapi di masyarakat juga sebuah fakta yang mesti dihadapi. Karena, konflik antara benar dan salah, jujur dan bohong, dan sejenisnya, tiada mengenal ruang dan waktu laksana hitam dan putih yang selain saling meniadakan juga saling mempertegas dan adakalanya saling melengkapi seperti papan catur yang padu-padan karena harmoni kedua warna tersebut. Lantas, mestikah mengorbankan idealisme hanya untuk diterima di masyarakat? Tak adakah jalan keluar untuk bisa eksis di masyarakat tanpa perlu menggadaikan idealisme, bahkan menjual murah dengan diskon besar-besaran?
Laboratorium Raksasa
Masyarakat adalah sebuah laboratorium raksasa. Disinilah segala teori akan diuji. Disinilah nyali akan dihadapkan pada fakta-fakta yang tak jarang berbeda seratus delapan puluh derajat dengan analisa. Maka, siapapun yang memilih terjun di masyarakat, pasti akan menjumpai hal-hal tersebut di atas, dengan bentuk dan wujud yang beragam. Ibarat tempat magang, di laboratorium raksasa itulah setiap peserta dilatih untuk mengenali aneka persoalan sekaligus disodori beragam alternatif solusinya lengkap dengan segala resikonya, termasuk dengan resiko-resiko yang sulit diprediksi. Maka, teorinya, mereka yang telah mengikuti pelatihan akan memiliki bekal minimal yang tentu saja, akan berbeda dengan mereka yang sama sekali tak pernah mengikutinya. Generasi muda yang telah, atau setidaknya pernah menjalani pelatihan, sedikit banyak akan memiliki bekal manakala mereka kelak akan menjadi pemimpin.
Calon-calon pemimpin yang telah teruji di masyarakat kemungkinan besar telah memiliki modal dasar, minimal pernah berhadapan langsung dengan aneka karakter dan tipikal individu yang beragam latar belakang. Juga akrab dengan beragam konflik dan persoalan riil yang telah dan tengah dihadapi oleh masyarakat. Di titik inilah ia belajar dan diajari oleh kenyataan. Maka, manakala keluh kesah dan problematika masyarakat beserta aneka opsi solusinya telah sedemikian dekat dengan urat nadinya, kelak, andaikata ia berganti posisi, hijrah dari bawahan menjadi atasan, dari rakyat jelata menjadi pemimpin bangsa, Insya Allah ia akan tahu bagaimana menempatkan dirinya di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Insya Allah ia akan tahu bagaimana dulu ia dan masyarakat memiliki harapan-harapan kepada pemimpinnya, dan kini di pundaknyalah harapan-harapan itu dititipkan. Laksana guru, ia pernah menjadi murid. Ia paham betul bagaimana rasanya menjadi murid beserta segala penilaiannya terhadap aneka sosok guru yang pernah mendidiknya. Laksana sopir, ia pernah menjadi kernet sehingga sedikit banyak ia tahu bagaimana memperlakukan kernet sebagaimana ia dulu ingin diperlakukan.
Lantas, untuk menjadi sopir yang baik, mestikan setiap calon sopir menjadi kernet terlebih dahulu? Tentu tidak. Dalam praktiknya, asal telah memenuhi syarat normatif, seperti cakap mengemudi, memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan sejenisnya, siapapun bisa menjadi sopir. Tetapi, bila kita dihadapkan pada dua kandidat dengan syarat normatif yang sama: sopir alumni sekolah mengemudi terkemuka yang baru lulus dan sopir yang telah kenyang pengalaman, benarkah kita akan memilih kandidat pertama, dan bukan kandidat kedua?
Pengalaman bukanlah segalanya. Tetapi, dari orang-orang yang telah berpengalaman di bidangnya, rasanya tidak berlebihan bila kita lebih mantap menitipkan amanah pada mereka. Mereka yang lahir dari ”rahim” masyarakat, hidup dan dihidupi oleh konflik, besar dan dibesarkan oleh denyut nadi kehidupan nyata, berkeringat dan bahkan menangis bersama derita banyak orang, berpeluang lebih besar untuk menjadi pemimpin yang memiliki empati, simpati, dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya daripada pemimpin yang lahir dari ujung tongkat tukang sulap, dengan iringan mantra sim salabim disertai kepulan asap dan tiba-tiba hadir serta duduk di singgasana kepemimpinan.
Pemimpin yang telah tertempa oleh pengalaman, dalam lingkup yang paling kecil sekalipun, memiliki pengetahuan minimal atas orang-orang yang dipimpinnya, sebagaimana ia dulu berada pada posisi tersebut. Ia bukanlah orang yang gila jabatan karena sejarah panjangnya telah mengajarinya bagaimana ia dulu tak bisa menghargai dan menghormati pemimpin-pemimpinnya yang menjadi gila karena jabatannya. Ia tahu betul bagaimana bertindak secara benar diantara ketidakbenaran sebagaimana dulu pemimpin-pemimpinnya melakukan ketidakbenaran tersebut. Di bawah kepemimpinan mereka yang memahami pahit getirnya kehidupan, sakitnya dikhianati, dan perihnya dizalimi, serta pada saat yang bersamaan juga memahami jalur yang tepat arah lokomotif yang dikemudikannya, orang-orang yang dipimpinnya akan merasa tenang dan nyaman. Manakala mereka telah meyakini bahwa pemimpin mereka adalah orang yang benar, pada saat yang benar, dan di tempat yang benar, kemungkinan besar mereka pun akan menempatkan diri pada posisi serupa, loyalitas sepenuh hati dan berdedikasi tinggi.
Bersambung

Pemimpin Redaksi
(Dirangkum dari artikel berjudul ”Belajar dari Ali bin Abi Thalib” yang diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis Pemuda Tingkat Nasional dan Penghargaan untuk Penulis Artikel Kepemudaan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Forum Lingkar Pena/FLP, Mei 2009)
Tak lama berselang, muncullah seorang tokoh agama. Setelah mengamati keadaan sang kakek, tokoh agama itu berujar, ”Mohon maaf, Kek. Saya ingin menolong kakek tapi saya telah ditunggu oleh jama’ah saya yang telah menanti sejak tadi. Ini pengajian bulanan jadi mereka telah menunggu sebulan lamanya untuk mendengarkan ceramah saya. Kakek tenang saja, nanti pasti ada orang lewat yang akan menolong kakek. Permisi.” Dan pergilah sang tokoh meninggalkan kakek sendirian.
Beberapa saat kemudian, lewatlah di jalan tersebut seorang pemulung berbaju lusuh. Mendengar rintihan meminta tolong, pemulung itu bergegas mendekat, kantong plastik dan batang besi dicampakkannya ke tanah, dan segera menolong kakek tersebut serta membawanya ke rumah penduduk terdekat. Setelah memastikan sang kakek mendapat pertolongan, pemulung itu mengambil barang-barangnya dan kembali meneruskan pekerjaannya: mencari sampah yang bisa dijual untuk membeli beras dan lauk untuk anak dan istrinya yang setia menunggu di rumah.
Momen yang Tepat
Ada hal mendasar yang ingin penulis sampaikan melalui ilustrasi di atas, yaitu momen. Tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih memilih untuk melayani masyarakat yang menunggu mereka dengan dalih bahwa menolong kakek itu bukanlah momen yang tepat. Selain urusan masyarakat yang mereka anggap lebih penting daripada sekadar menolong seorang kakek, mereka meyakini bahwa akan datang orang lain yang akan melakukan pekerjaan itu.
Momen yang tepat. Itulah kata sakti yang sering ditunggu oleh banyak orang untuk melakukan sesuatu, tidak terkecuali oleh generasi muda. Seringkali kita temui generasi muda, yang umumnya terdidik, yang belum juga mau terjun ke masyarakat karena ”menunggu momen yang tepat”. Pilihan yang tidak sepenuhnya salah. Tetapi, perlu juga disadari bahwa proses menunggu tidak lantas membuat jarum jam berhenti berdetak sementara gerak dan geliat dinamika masyarakat amatlah dinamis.
Di sisi lain, terkadang juga kita temui generasi muda yang pada akhirnya lebih memilih mundur dari ”gelanggang pertempuran” dengan dalih bahwa masyarakat telah terlanjur rusak sehingga ia yang mencoba hadir sebagai agent of change, agen perubahan-sebutan yang amat dibanggakan hasil produksi kampus-ternyata tak mampu merubah apapun di masyarakat. Idealisme yang dibawa dari kampus nan megah, sumber referensi dari aneka buku, diktat, modul, dan karya ilmiah, serta teori-teori panjang lebar yang dengan susah payah telah dihafalkan, ternyata menjadi teramat abstrak manakala hendak diimplementasikan di kehidupan nyata.
Di kampus, yang haru-biru oleh gegap gempita semangat perubahan lengkap dengan teriakan dan acungan tangan mengepal, idealisme adalah kenyataan. Dan merupakan sebuah harga mati yang tak lagi bisa ditawar. Di masyarakat? Aneka kenyataan kemudian seringkali berujung pada kesimpulan singkat: untuk bertahan hidup, kenyataan adalah idealisme. Dan tenggelamlah sang agen perubahan pada pertempuran batin yang nyaris tanpa jeda. Tanpa ujung. Tidak sedikit yang menyerah kalah dan terkapar di titik frustrasi.
Tak adakah celah di antara dua pilihan itu? Apakah pilihan untuk memperjuangkan idealisme di masyarakat adalah semata-mata pilihan antara benar dan salah, antara hitam dan putih? Menurut penulis, ada. Memperjuangkan idealisme memang sebuah keniscayaan. Tetapi, kenyataan yang dihadapi di masyarakat juga sebuah fakta yang mesti dihadapi. Karena, konflik antara benar dan salah, jujur dan bohong, dan sejenisnya, tiada mengenal ruang dan waktu laksana hitam dan putih yang selain saling meniadakan juga saling mempertegas dan adakalanya saling melengkapi seperti papan catur yang padu-padan karena harmoni kedua warna tersebut. Lantas, mestikah mengorbankan idealisme hanya untuk diterima di masyarakat? Tak adakah jalan keluar untuk bisa eksis di masyarakat tanpa perlu menggadaikan idealisme, bahkan menjual murah dengan diskon besar-besaran?
Laboratorium Raksasa
Masyarakat adalah sebuah laboratorium raksasa. Disinilah segala teori akan diuji. Disinilah nyali akan dihadapkan pada fakta-fakta yang tak jarang berbeda seratus delapan puluh derajat dengan analisa. Maka, siapapun yang memilih terjun di masyarakat, pasti akan menjumpai hal-hal tersebut di atas, dengan bentuk dan wujud yang beragam. Ibarat tempat magang, di laboratorium raksasa itulah setiap peserta dilatih untuk mengenali aneka persoalan sekaligus disodori beragam alternatif solusinya lengkap dengan segala resikonya, termasuk dengan resiko-resiko yang sulit diprediksi. Maka, teorinya, mereka yang telah mengikuti pelatihan akan memiliki bekal minimal yang tentu saja, akan berbeda dengan mereka yang sama sekali tak pernah mengikutinya. Generasi muda yang telah, atau setidaknya pernah menjalani pelatihan, sedikit banyak akan memiliki bekal manakala mereka kelak akan menjadi pemimpin.
Calon-calon pemimpin yang telah teruji di masyarakat kemungkinan besar telah memiliki modal dasar, minimal pernah berhadapan langsung dengan aneka karakter dan tipikal individu yang beragam latar belakang. Juga akrab dengan beragam konflik dan persoalan riil yang telah dan tengah dihadapi oleh masyarakat. Di titik inilah ia belajar dan diajari oleh kenyataan. Maka, manakala keluh kesah dan problematika masyarakat beserta aneka opsi solusinya telah sedemikian dekat dengan urat nadinya, kelak, andaikata ia berganti posisi, hijrah dari bawahan menjadi atasan, dari rakyat jelata menjadi pemimpin bangsa, Insya Allah ia akan tahu bagaimana menempatkan dirinya di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Insya Allah ia akan tahu bagaimana dulu ia dan masyarakat memiliki harapan-harapan kepada pemimpinnya, dan kini di pundaknyalah harapan-harapan itu dititipkan. Laksana guru, ia pernah menjadi murid. Ia paham betul bagaimana rasanya menjadi murid beserta segala penilaiannya terhadap aneka sosok guru yang pernah mendidiknya. Laksana sopir, ia pernah menjadi kernet sehingga sedikit banyak ia tahu bagaimana memperlakukan kernet sebagaimana ia dulu ingin diperlakukan.
Lantas, untuk menjadi sopir yang baik, mestikan setiap calon sopir menjadi kernet terlebih dahulu? Tentu tidak. Dalam praktiknya, asal telah memenuhi syarat normatif, seperti cakap mengemudi, memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan sejenisnya, siapapun bisa menjadi sopir. Tetapi, bila kita dihadapkan pada dua kandidat dengan syarat normatif yang sama: sopir alumni sekolah mengemudi terkemuka yang baru lulus dan sopir yang telah kenyang pengalaman, benarkah kita akan memilih kandidat pertama, dan bukan kandidat kedua?
Pengalaman bukanlah segalanya. Tetapi, dari orang-orang yang telah berpengalaman di bidangnya, rasanya tidak berlebihan bila kita lebih mantap menitipkan amanah pada mereka. Mereka yang lahir dari ”rahim” masyarakat, hidup dan dihidupi oleh konflik, besar dan dibesarkan oleh denyut nadi kehidupan nyata, berkeringat dan bahkan menangis bersama derita banyak orang, berpeluang lebih besar untuk menjadi pemimpin yang memiliki empati, simpati, dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya daripada pemimpin yang lahir dari ujung tongkat tukang sulap, dengan iringan mantra sim salabim disertai kepulan asap dan tiba-tiba hadir serta duduk di singgasana kepemimpinan.
Pemimpin yang telah tertempa oleh pengalaman, dalam lingkup yang paling kecil sekalipun, memiliki pengetahuan minimal atas orang-orang yang dipimpinnya, sebagaimana ia dulu berada pada posisi tersebut. Ia bukanlah orang yang gila jabatan karena sejarah panjangnya telah mengajarinya bagaimana ia dulu tak bisa menghargai dan menghormati pemimpin-pemimpinnya yang menjadi gila karena jabatannya. Ia tahu betul bagaimana bertindak secara benar diantara ketidakbenaran sebagaimana dulu pemimpin-pemimpinnya melakukan ketidakbenaran tersebut. Di bawah kepemimpinan mereka yang memahami pahit getirnya kehidupan, sakitnya dikhianati, dan perihnya dizalimi, serta pada saat yang bersamaan juga memahami jalur yang tepat arah lokomotif yang dikemudikannya, orang-orang yang dipimpinnya akan merasa tenang dan nyaman. Manakala mereka telah meyakini bahwa pemimpin mereka adalah orang yang benar, pada saat yang benar, dan di tempat yang benar, kemungkinan besar mereka pun akan menempatkan diri pada posisi serupa, loyalitas sepenuh hati dan berdedikasi tinggi.
Bersambung

Pemimpin Redaksi
(Dirangkum dari artikel berjudul ”Belajar dari Ali bin Abi Thalib” yang diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis Pemuda Tingkat Nasional dan Penghargaan untuk Penulis Artikel Kepemudaan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerja sama dengan Forum Lingkar Pena/FLP, Mei 2009)

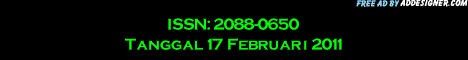

 Cetak
Cetak
0 komentar:
Posting Komentar