Oleh: Dzakiron
Enam tahun mengenyam pendidikan SD, enam tahun di tingkat menengah dua tahun pada jenjang diploma, dan sekarang pada semester dua jenjang strata satu, mempertemukan saya dengan beragam rupa, cara, dan metode pengajaran guru. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, hampir semuanya menjadi sumber inspirasi dan referensi manakala kini harus berganti posisi: hijrah dari murid menjadi guru.
Baru lima tahun menjalani profesi bertitel Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini, saya menyadari, betapa tidak mudahnya menjadi seorang guru. Dengan jam terbang yang masih sangat sedikit tersebut, betapa sulitnya mengajarkan aneka norma dan nilai mulia di depan kelas dan pada saat yang bersamaan profesi itupun menuntut saya untuk mempraktikkannya. Manakala mendapati siswa yang bandel, tidak mengerjakan PR, dan aneka tingkah laku yang membuat saya menghela napas panjang, saya merasa sedang memutar mundur jarum jam ke titik sekian waktu manakala saya duduk di bangku itu, dulu.
Dalam setiap pertemuan di kelas, rata-rata siswa SD menempuhnya dalam waktu 2 x 35 menit untuk dua jam pelajaran. Itu berarti 70 menit alias 1 jam 10 menit. Saya sendiri sudah tidak terlalu ingat bagaimana persisnya dulu saya melewatkan waktu sepanjang itu dalam mengikuti pelajaran. Yang saya ingat, ada pelajaran yang saya ikuti dengan sepenuh hati karena bagi saya, dan juga teman-teman, gurunya menyenangkan karena jarang marah, seringkali membuat kami tertawa, dan tidak membuat tangan kami pegal-pegal karena terlalu sering menulis. Dan ada juga pelajaran yang saya ikuti dengan perasaan sebaliknya seraya menggerutu, mengapa bel tanda istirahat tak juga berbunyi.
Maka, sulit saya bayangkan dalam situasi nyata ketika sosok-sosok mungil tak berdosa, yang sejak awal mereka masuk sekolah telah diperkenalkan bahwa guru adalah orang tua di sekolah, kemudian mesti mendapati kenyataan sebaliknya: sosok-sosok angker nan mengerikan yang menebarkan teror dan ketakutan dengan kalimat-kalimat bernada ancaman atau bahkan hukuman-hukuman fisik di luar batas kewajaran. Lebih tragis lagi, berperilaku amoral dan asusila. Masya Allah.
Jendela kelas dan aneka bentuk ventilasi lainnya, yang didoktrinkan di buku pelajaran sebagai sarana pertukaran udara yang menyehatkan, menjelma menjadi terali besi yang memisahkan mereka dengan ruang bebas di luar sana. Gerak jarum jam dinding usang di atas papan tulis serasa amat lambat. Bunyi bel tanda istirahat atau pulang adalah suara ketukan palu hakim dengan vonis bebas.
Saya tak bermaksud mendramatisir suasana. Sama sekali tidak. Saya hanya mengingat sebuah momen kala Ilzama Maula Wafda Sabila, putri saya, yang saat itu berusia empat tahun (kini berumur lima tahun enam bulan) memporak-porandakan kertas kerja di meja komputer pada suatu hari. Reflek, saya berkata ”Jangan!” dengan nada yang lumayan tinggi. Masya Allah, dalam beberapa detik, saya saksikan efek yang amat dahsyat. Si Kecil bergegas menghambur ke pelukan ibunya, dan sesaat kemudian saya mendengar isak tangis yang tertahan. Tersadar, saya segera memburunya, mencoba mengelus bahunya seraya meminta maaf atas ketidaksengajaan tadi. Tetapi, bahasa tubuhnya menunjukkan penolakan dan tangisnya semakin menjadi. Setelah tangisnya mereda, ia masih membutuhkan waktu beberapa waktu sebelum kembali mendekati saya di meja komputer untuk kemudian kembali ceria seperti tak pernah terjadi apa-apa.
Maka, membayangkan situasi di kelas dimana menit demi menit berlalu dalam cekaman ketakutan, pergantian mata pelajaran demi mata pelajaran yang tidak menyisakan apapun selain tambahan tugas dan PR hukuman, serta lontaran kalimat-kalimat yang sangat tidak nyaman didengar, sungguh membuat dada saya sesak. Dada saya semakin terasa sesak ketika media massa mengabarkan tentang hukuman fisik terhadap siswa yang menurut saya jauh dari tujuan mendidik. Apalagi ketika calon-calon pelaku sejarah itu diberitakan mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari gurunya. Mereka? Anak-anak kecil itu? Ah.....
Meski kasus-kasus tersebut adalah insidental, yang sangat-sangat tidak bijak dan jelas tidak bisa digeneralisasi bahwa semua guru juga berperilaku dan melakukan hal yang sama, setidaknya kita tahu bahwa hal tersebut ada, sungguh-sungguh terjadi, dan benar-benar hadir sebagai sebuah mimpi buruk dunia pendidikan.
Kita sadari bersama, ada kondisi-kondisi ideal yang belum terwujud. Ada keadaan yang belum sesuai harapan. Masih ada (atau mungkin banyak) Guru Wiyata Bhakti/Pengabdian yang menerima honor jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Masih ada dikotomi PNS-Non PNS. Belum semua gedung sekolah mendapat penanganan maksimal. Mungkin juga ”Tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen ingin kawin, bisa rubuh berantakan” sebagaimana dideskripsikan oleh Andrea Hirata dalam Laskar Pelangi halaman 17. Gambaran kondisi SD Muhammadiyah di Belitong, pelosok Sumatera Selatan dalam buku bestseller yang pada Bulan Oktober 2007 telah cetak ulang kesepuluh dan pada Bulan Desember 2007 kembali naik cetak yang kelima belas tersebut belumlah utuh, karena sekolah itu ”.... Tak pernah dikunjungi pejabat, penjual kaligrafi, pengawas sekolah, apalagi anggota dewan”. (hal. 18). Ruang kelasnya? ”Di dalam kelas kami tidak terdapat tempelan poster operasi kali-kalian seperti umumnya terdapat di kelas-kelas sekolah dasar. Kami juga tidak memiliki kalender dan tak ada gambar presiden dan wakilnya, atau gambar seekor burung aneh berekor delapan helai yang selalu menoleh ke kanan itu" (hal. 19).
Bagaimana dengan gurunya? SD tersebut memiliki dua orang guru. Pertama, Pak Harfan. Nama lengkapnya: Harfan Efendy Noor. Sebagai Kepala Sekolah, Pak Harfan telah puluhan tahun mengabdi di sekolah Muhammadiyah nyaris tanpa imbalan apa pun demi motif syiar Islam. Di hari pertama tahun ajaran baru, Pak Harfan ”... mengenakan baju takwa yang dulu pasti berwarna hijau tapi kini warnanya pudar menjadi putih. Bekas-bekas warna hijau masih kelihatan di baju itu. Kaus dalamnya berlubang di beberapa bagian dan dan beliau mengenakan celana panjang yang lusuh karena terlalu sering dicuci.” (hal. 21).
Guru kedua, Bu Muslimah Hafsari atau Bu Mus, yang ”...diupah beras 15 kilo setiap bulan”. Setelah mengajar, ”...beliau melanjutkan bekerja menerima jahitan sampai jauh malam untuk mencari nafkah, menopang hidup dirinya dan adik-adiknya.” (hal. 30).
Sekarang, lihatlah potret murid-muridnya. Satu diantara sepuluh murid kelas satu adalah Lintang, si jenius yang pulang pergi naik sepeda; melewati jalan kerikil batu merah empat puluh kilometer. Setibanya di sekolah, tercium bau hangus dari alas kakinya, yaitu ”...sandal cunghai, yaitu sandal yang dibuat dari ban mobil, yang aus karena Lintang terlalu jauh mengayuh sepeda.” (hal. 11)
Mungkin deskripsi tersebut mewakili kondisi riil wajah mengenaskan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah Nusantara. Memilukan? Ya. Tapi, tunggu dulu. Dari ruang kelas yang tak punya kotak P3K itu, lihatlah bagaimana murid-murid, yang terwakili oleh aku, menggambarkan guru-gurunya. Bu Mus, misalnya, adalah ”seseorang yang bersedia menerima kami apa adanya dengan sepenuh hatinya, segenap jiwanya.” Sedangkan Pak Harfan: ”...tampak amat bahagia menghadapi murid, tipikal ”guru” yang sesungguhnya, seperti dalam lingua asalnya, India, yaitu orang yang tak hanya mentransfer sebuah pelajaran, tapi yang juga secara pribadi menjadi sahabat dan pembimbing spiritual bagi muridnya.” (hal. 24)
Dengan minimnya fasilitas, kita bisa membayangkan prosesi kegiatan belajar mengajar (KBM) setiap harinya. Tapi, di tangan kedua guru yang menjadi ksatria tanpa pamrih, pangeran keikhlasan, dan sumur jernih ilmu pengetahuan di ladang yang ditinggalkan (hal. 32), lahirlah kedahsyatan-kedahsyatan yang semestinya membuat kita; yang telah, tengah, dan masih saja meratapi aneka kekurangan yang didalilkan sebagai penyebab ketiadaan prestasi, menurunnya dedikasi dan etos kerja; malu. Lihatlah Lintang, yang begitu bersemangat mengikuti pelajaran sampai ia pun berteriak: ”Tak mau Ibunda, pagi ini ketika berangkat sekolah aku hampir diterkam buaya, maka aku tak punya waktu menunggu, jelaskan di sini, sekarang juga!” manakala Bu Mus mengatakan bahwa ilmu tafsir baru akan diajarkan di kelas dua SMP. (Hal. 111).
”Aku merasa telah terselamatkan karena orangtuaku memilih sebuah sekolah Islam sebagai pendidikan paling dasar bagiku. Aku merasa amat beruntung berada di sini, di tengah orang-orang yang luar biasa ini. Ada keindahan di sekolah Islam melarat ini. Keindahan yang tak ’kan kutukar dengan seribu kemewahan sekolah lain. .....” (Hal. 25) Itulah kesan pertama sang aku di hari pertama pelajaran, manakala Pak Harfan menerangkan tentang Perang Badar, dimana tiga ratus tiga belas tentara Islam mengalahkan ribuan tentara Quraisy yang kalap dan bersenjata lengkap; dan tentang perjuangan para penegak Islam lainnya. ”Ada semacam pengaruh yang lembut dan baik terpancar darinya. Ia mengesankan sebagai pria yang kenyang akan pahit getir perjuangan dan kesusahan hidup, berpengetahuan seluas samudra, bijak, berani mengambil resiko, dan menikmati daya tarik dalam mencari-cari bagaimana cara menjelaskan sesuatu agar setiap orang mengerti.” (hal. 23).
Manakala Pak Harfan harus mohon diri karena jam pelajaran telah usai, aku pun berbisik kecewa ”....Satu jam dengannya terasa hanya satu menit....” (hal. 25).
Membaca kalimat terakhir, tengkuk saya mendadak terasa dingin. Sangat dingin. Andaikata mampu, saya ingin menelusup ke relung hati murid-murid saya manakala saya mengucapkan salam untuk mengakhiri pelajaran. Ingin saya baca dari hati mereka kalimat pengantar yang mengiringi kaki saya meninggalkan kelas.
Apakah mereka membisikkan kata-kata serupa? Atau sebaliknya: satu menit dengannya terasa satu jam? Apakah mereka terburu-buru berangkat sekolah karena merindukan celotehan saya di depan kelas, ataukah karena mereka ngeri atas hukuman fisik karena keterlambatan? Dan manakala saya kembali memasuki kelas keesokan harinya, apakah hati mereka bersorak girang karena bertemu lagi dengan kakak sekaligus sahabat yang mendampingi mereka dengan simpati, empati dan keramahan sepenuh hati; ataukah mereka sesungguhnya menunjukkan kepatuhan semu karena di depan mereka berdiri dengan angkuhnya sosok angker yang menebarkan teror dan ketakutan?
------------------------------------------------------
Selamat Menyongsong dan Memaknai Tahun Ajaran Baru 2010/2011. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin.....
------------------------------------------------------
Catatan:
Artikel ini dikirimkan ke Redaksi Derap Guru Jawa Tengah via e-mail pada 21 Agustus 2009 kala saya masih bertugas di SD Negeri 01 Paninggaran. Di-posting dengan sedikit tambahan dan editing
Minggu, 11 Juli 2010
 BELAJAR DARI ”LASKAR PELANGI”
BELAJAR DARI ”LASKAR PELANGI”
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

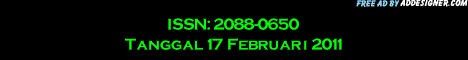

 Cetak
Cetak
Ya kita bisa banyak belajar dari laskar pelangi, bahwa guru harus menjadi INSPIRATOR dan MOTIVATOR bagi anak didiknya..... Selamt untuk terus bermakna dan memberi inspirasi bagi generasi penerus kita......
BalasHapusMantap...
BalasHapusBerjuanglah guru-guru...
Kalau gitu sy mau jadi guru aja...
hehehe...
Subhanallaah. Terima kasih pak atas inspirasinya.
BalasHapusAlhamdulillah bila bisa menjadi sesuatu yg bermanfaat. Terima kasih kembali atas kunjungannya
BalasHapus