Saat itu sekolahku lulus seratus persen, dengan aku menjadi bagian dari kelulusan. Kami semua berteriak dalam kegembiraan, tetapi anehnya kenapa masih ada kesedihan diam-diam.
Aku menyangka kesedihan itu bersumber dari perpisahan kami dari kenangan: dari sekolah, guru-guru, teman-teman, dan penjaga. Soal-soal yang semula biasa-biasa saja, baru ketika hendak berpisah, semuanya menjadi muncul dan berharga.
Saat itu, imajinasi kesedihanku baru sebatas menjangkau wilayah itu, tetapi tidak kini. Ada lagi agaknya sumber kesedihanku yang pelan-pelan terbaca di saat ini. Dulu sumber kesedihan ini tersimpan dalam, tanpa aku tahu, tetapi terus terasakan. Terasa tapi tidak tahu, itulah yang membingungkan.
Kini, tanpa ragu aku menebak sumber kesedihan misterius itu, ia tak lain adalah nilai matematika di ijazahku. Nilai itu cuma enam, terjelek di antara seluruh nilaiku. Aku menyangka nilai ini muncul lantaran kebencian guru matematikaku kepadaku. Diam-diam aku marah sekali pada guru itu. Nilai enam ini adalah noda di ijazahku yang akan terpatri di situ nyaris selamanya. Sekian lama aku sakit oleh nilai itu karena dan hampir saja aku menolak untuk melihat ijasah itu.
Kini aku malu sekali pada prasangkaku. Guru itu ternyata adalah guru yang amat baik kepadaku. Seorang guru lain diam-diam meyakinkanku, jika ukurannya adalah hasil ujian asli, nilai matematika bukan enam, tapi empat. Angka enam itu ternyata sudah terlalu tinggi untuk kemampuanku dan guru itulah yang membelaku. Jika cuma mengandalkan hasil ujian, aku adalah murid yang tidak lulus.
Itulah kenapa, meskipun aku ikut-ikutan bergembira, tetap saja ada kesedihan tersembunyi di hatiku. Karena ternyata kelulusan itu sejatinya bukan milikku. Itulah kenapa kebohongan itu tak bisa lenyap dari hati walau tak ada orang yang tahu. Menikmati sesuatu yang bukan milikku ternyata hanya kegembiraan semu.
Dan nilai ijazah palsu itu ternyata memang hanya kuat membelaku seperti nilai aslinya, cuma empat itu sajalah, sesuai dengan kemampuanku. Buktinya seluruh sekolah lanjutan yang kuanggap favorit, yang kusangka sesuai dengan derajatku, semuanya menolakku. Semua sekolah itu pasti membutuhkan nilai delapan asli untuk lulus seleksi, bukan nilai enam itu pun palsu.
Akhirnya, satu-satunya sekolah yang mau menerimaku adalah sebuah sekolah baru yang sedang butuh murid, yang masuk sore pulang petang dengan gedung menginduk, itupun bobrok pula.
Tak terkira rasa rendah diriku jika harus berpapasan dengan anak-anak yang masuk pagi. Ketika mereka pulang kami berangkat dan dari pandangan mereka aku tahu, mereka mencibirku. Keterbalikan jadwal ini sungguh setara rasanya dengan keterbalikkan nasibku. Tetapi beginilah memang mestinya murid dengan nilai empat ini. Bahkan masih ada sekolah yang mau menerimaku pun mestinya sudah sebuah anugerah.
Tapi di sekolah bobrok inilah ternyata aku menemukan teman-teman terbaik, guru-guru terbaik, lingkungan terbaik dan banyak sekali kebaikan lain yang tak pernah aku bayangkan. Begitu menyadari nilaiku cuma empat, dan cuma sekolah inilah yang mau menerimaku, rasa cintaku pada sekolah ini tumbuh pelan dan pasti.
Akhirnya seluruh usaha kupompakana agar yang empat ini menjadi enam, tujuh dan seterusnya, sekuatku, sebisaku, yang penting aku tidak lagi menipu. Ternyata, menyangkut soal nilai ijazah itu, yang paling berharga bukanlah besarannya, melainkan kejujurannya. Empat yang kuterima sebagai keaslikanku ternyata jauh lebih berguna katimbang enam tapi palsu.
(Prie GS/bnol)
Sumber: Merenung Sampai Mati (Unofficial PRIE GS Blogs)
Catatan:
Terima kasih banyak buat Mas Prie GS yang tetap berkarya dengan hati. Artikel "Berdialog dengan Derita" yang dimuat di Serambi-nya Tabloid Cempaka Minggu Ini beberapa tahun silam masih terpajang di ruang kerja saya sampai sekarang. Teruslah berkarya, bang...
Senin, 05 Juli 2010
 LULUS SERATUS PERSEN
LULUS SERATUS PERSEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

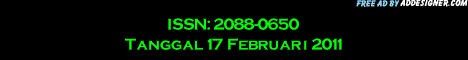

 Cetak
Cetak
0 komentar:
Posting Komentar