MEMBERI ATAU MENJADI CONTOH?
Oleh:
DZAKIRON
Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
SD Negeri Tanggeran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan
Sesuai dengan fitrahnya, setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Dengan keluguan dan kepolosannya, ia laksana kertas putih yang akan memiliki warna dan corak sesuai dengan yang digoreskan padanya. Rasa keingintahuannya yang besar dan kemampuan analisisnya yang belum berkembang, cenderung menyebabkan anak meniru segala yang dilihat dan didengarnya. Mata si anak melihat dan merekam apa saja yang tampak olehnya. Rekaman tersebut tinggal lama dalam ingatan, sehingga, menurut Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, ada pakar kejiwaan yang mengatakan bahwa manusia belajar lewat penglihatannya sebanyak 83%. Melalui pendengarannya, anak belajar sebanyak 11%. Sedangkan sentuhan, pencicipan, dan penciuman bersama-sama memberi pengaruh sebanyak 6%. Jadi pengaruh terbesar adalah lewat penglihatan dan pendengaran, yaitu 94% (Zakiah Daradjat, 1995:56).
Oleh karena itu, apabila sejak usia 3 tahun anak mulai diperkenalkan dan diarahkan kepada nilai-nilai moral, hal itu tentunya akan mempermudah pembentukan pribadi anak yang kelak akan memiliki keunggulan akhlak yang mulia.
Empati, simpati, dan bentuk-bentuk kecerdasan emosional lainnya, bila berpadu dengan kejujuran yang tertanam kuat sejak dini, akan mempermudah anak untuk diterima di lingkungannya, disamping tentu saja akan menjadi modal dasar yang sangat berharga bagi anak untuk hidup di masyarakat. Ini berarti, selain pembawaan, lingkungan dimana anak dibesarkan, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan diri dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan Hukum Konvergensi yang berasal dari pendapat ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, William Stern, bahwa pembawaan dan lingkungan, kedua-duanya menentukan perkembangan manusia (Ngalim Purwanto, 1998:60).
Benih Kebohongan
Sesungguhnya, dari mana anak memperoleh benih kebohongan atau ketidakjujuran? Mari kita telusuri sejenak. Terkadang, anak menyatakan keinginannya untuk ikut bapak atau ibunya ke suatu tempat, seperti pasar, pesta hajatan, dan sebagainya. Untuk sekadar menyurutkan keinginan sang anak, maka, kemungkinan jawaban orang tua adalah: “Jangan, nanti ada orang gila di sana”, “Nanti disuntik pak dokter, lho”, “Kalau kamu ikut nanti ditangkap pak polisi”, atau jawaban-jawaban sejenis lainnya yang sekiranya membuat anak menjadi takut dan mengurungkan niatnya.
Memasuki bangku sekolah dasar, lambat laun ia mengetahui bahwa di pasar, atau di tempat lain yang selama ini disebut-sebut oleh orang tuanya, ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh orang tuanya. Tidak ada dokter yang akan menyuntiknya secara paksa. Juga tidak ada polisi yang akan menangkapnya. Selain menumbuhkan ketakutan tersendiri terhadap dokter dan polisi, disadari atau tidak, orang tua telah mengajari anaknya untuk berbohong. Lebih fatal lagi apabila sang anak juga menyadari, kelak suatu saat, bahwa ia telah sekian lama dibohongi oleh orang tuanya.
Pada saat orang tuanya menyuruh anak untuk mengatakan kepada petugas penarik sumbangan, pengamen, atau pengemis, bahwa orang tuanya sedang tidak berada di rumah, ia mulai belajar mempraktikkan ilmu itu manakala ia ingin memiliki mainan baru atau untuk membeli jajan tambahan sementara uang sakunya tak pernah lebih. Dengan mengatakan bahwa uang untuk menabung telah hilang, ia pun bisa memenuhi keinginannya. Dan perlahan-lahan, teknik-teknik berbohong dengan cara-cara yang lebih canggih dan relatif lebih aman mulai ia pelajari dari pengalaman sehari-hari. Contoh-contoh yang diperagakan oleh orang-orang di sekelilingnya akan menjadi referensi berharga untuknya, yang dapat berujung pada kesimpulan sederhana: ternyata, berbohong itu mudah. Orang tua mungkin tak menyadari, dari titik inilah benih kebohongan telah bersemi dan potensinya siap untuk “dibudidayakan” (Dzakiron, 2008:4).
Keteladanan dan Standar Ganda Orang Tua
Anak adalah peniru yang baik. Nilai moral yang ditanamkan oleh orang tua, termasuk guru di dalamnya, akan kurang (atau bahkan tidak) berarti bila bertolak belakang dengan tingkah laku orang tua. Akan menjadi upaya sia-sia belaka apabila orang-orang yang semestinya menjadi teladan justru melakukan tindakan yang kontraproduktif dengan ajaran-ajarannya sendiri.
Di sinilah orang tua kerapkali terjebak pada upaya formalitas: memberi contoh. Dalam konteks pendidikan formal, tak jarang guru juga terjebak pada hal yang sama. Label digugu lan ditiru, di satu sisi memang memberikan nilai prestise tersendiri bahwa guru adalah sekelompok manusia yang memiliki tempat sosial tersendiri. Guru adalah sosok yang digambarkan selalu mengajarkan norma dan nilai kebaikan serta menjadi penjaga gawang dalam pendidikan moral anak didiknya. Juga wakil dari orang tua di sekolah. Kepadanyalah dititipkan harapan, diamanatkan segudang impian, dan tentu saja, disematkan gelar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
Di sisi lain, sulit menghindarkan kesan bahwa (ada) guru yang terbebani dengan figur yang senantiasa memberikan keteladanan. Akibatnya, ”penampakan” guru untuk tampil prima tersebut kerapkali terbungkus formalitas belaka: sekadar menunaikan kewajiban, sehingga tugas guru sebagai pengajar dan pendidik dianggap selesai manakala telah menyampaikan materi pelajaran. Lebih fatal lagi bila kemudian guru terjebak menempatkan diri pada posisi serba tahu, siaga dengan aturan–aturan keras, dan bahkan kadang teramat sakral untuk sekadar dikritik. Inilah implikasi dari penerapan standar ganda dimana guru mengajarkan beragam aturan dan norma lengkap dengan ancaman tegas serta hukuman atas pelanggaran, dan pada saat yang sama, guru justru melakukan tindakan–tindakan yang kontraproduktif dengan ajaran–ajaran itu. Mengajarkan kesopanan tapi duduk dengan manis di tepi meja siswa saat menerangkan pelajaran; mendoktrin etika berpakaian tapi mengenakan busana kerja yang ketat, rajin mengeluarkan ancaman hukuman atas keterlambatan tapi jarang hadir tepat waktu; dan sebagainya.
Yang pasti, dengan atau tanpa disadari, sebagai figur dimana terkadang ucapannya lebih dipatuhi anak didik daripada orang tuanya sendiri, segala perilaku dan tutur kata guru, adalah teladan bagi anak didiknya. Upaya menanamkan dan menumbuhsuburkan aneka norma mulia, termasuk kejujuran, menurut penulis, Insya Allah akan lebih mudah dilakukan manakala guru bertindak bukan hanya memberi contoh tetapi juga menjadi contoh.
Ajaran kejujuran, sebagai bekal pertama dan utama, akan memancarkan aura dan kharisma tersendiri manakala disampaikan oleh guru yang menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai falsafah dasar hidup dan kehidupannya. Atau, minimal, tidak mentradisikan dan melestarikan ketidakjujuran. Karena, semestinya, mengajarkan kejujuran kepada anak didik bukan hanya mendeskripsikan pengertian dan mendiktekan contoh kejujuran serta ketidakjujuran belaka, tetapi, yang lebih penting adalah menanamkan idealisme bahwa “Orang yang menghasilkan harta tanpa peduli dari mana, ia akan dimasukkan Allah ke neraka tanpa peduli dari pintu yang mana” sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Manshur Ad Dailami (Achmad Sunarto, 1989: 16). Penulis meyakini bahwa konsistensi penajaman materi akhlakul karimah, khususnya kejujuran dalam mata pelajaran pendidikan agama dan pengintegrasian dalam mata pelajaran lainnya, dari tingkat dasar sampai menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, akan semakin memperteguh keyakinan anak didik akan nilai mulia kejujuran. Pada gilirannya, out put pendidikan akan memiliki standar kejujuran lebih tinggi, yang diharapkan akan meminimalkan lahirnya koruptor-koruptor baru.
Kalaupun kelak ia berpredikat guru PNS, patutlah kita berharap bahwa ia tidak memanipulasi data untuk pemberkasan dalam pengangkatan CPNS, tidak korupsi waktu, menggunakan kendaraan bergincu alias berplat merah hanya untuk keperluan dinas, serta tidak mempertaruhkan idealismenya untuk meningkatkan karier, seperti mengajukan angka kredit, aneka kompetisi guru, seleksi kepala sekolah, dan belakangan, Sertifikasi Guru; dengan piagam, sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya yang (di)palsu(kan).
Dalam pengantar kidung Jagalah Hati, KH. Abdullah Gymnastiar (Aa’ Gym) bertutur: ”Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah, dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran”.
Bila kita menyepakati bahwa memberi contoh merupakan hal yang penting, maka semestinya kita pun tak butuh waktu lama untuk berdebat hanya untuk mencapai kata sepakat dan mufakat bahwa menjadi contoh itu jauh lebih penting. Setidaknya, agar mitos Undang–undang Kebenaran Guru, yang berbunyi : “Pasal satu: guru selalu benar; Pasal dua: bila guru salah, lihat pasal satu” tidak lagi menjadi perisai dan parit perlindungan, manakala kita, guru, sebagai manusia biasa, melakukan kesalahan dan kekeliruan.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional. ”Bangkitlah” guruku. Bangkitlah Indonesiaku. Bangkitlah!!! Referensi:
Al-Ghazali, Imam. Tanpa tahun. Halal dan Haram. Terjemahan oleh Achmad Sunarto. 1989. Jakarta: Pustaka Amani.
Daradjat, Zakiah. 1995. Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah. Jakarta: CV. Ruhama.
Purwanto, Ngalim. 1998. Psikologi Pendidikan. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
Dzakiron. 2008. Memutus Mata Rantai “Pendidikan Berbohong” Sebagai Benih Korupsi. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Agama Berbasis Nilai”, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Agama Islam (LKP2AI) STAIN Pekalongan, 30 Juni 2008. Baca juga di: Agupena Jawa Tengah

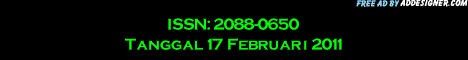

 Cetak
Cetak
0 komentar:
Posting Komentar